BENGKULU, Caribengkulu.com– Dalam epik Perang Jawa (1825-1830), salah satu babak terpenting perlawanan anti-kolonial di Nusantara, muncul sesosok komandan militer yang brilian, karismatik, sekaligus enigmatik: Sentot Ali Basya Abdullah Mustafa Prawirodirjo. Di usianya yang masih sangat muda, ia telah menjelma menjadi seorang panglima perang yang ditakuti, mendapatkan julukan "Napoleon Jawa" sebagai pengakuan atas kejeniusan taktiknya yang bahkan dikagumi oleh pihak musuh. Kehidupannya adalah sebuah epik yang dipenuhi dengan keberanian, strategi cerdik, dan kemenangan gemilang di medan laga.
Namun, narasi tentang Sentot Prawirodirjo jauh dari sekadar kisah kepahlawanan yang linear. Ia adalah personifikasi dari paradoks dan kompleksitas. Ia adalah seorang pejuang anti-kolonial yang pada akhirnya menyerah dan mengabdi di bawah panji-panji Belanda yang pernah diperanginya. Ia adalah seorang komandan Muslim yang taat, namun kemudian ditempatkan oleh Belanda dalam posisi untuk memerangi sesama Muslim dalam Perang Padri di Sumatera Barat. Ia adalah seorang tokoh yang jejak perjuangannya berakhir di pengasingan, namun warisannya justru bersemi dan mengakar kuat di tanah pembuangannya, Bengkulu, di mana makamnya kini dihormati sebagai Cagar Budaya Indonesia.
Meskipun perannya sangat sentral dalam Perang Jawa dan legasinya tetap hidup, nama Sentot Prawirodirjo secara mencolok tidak tercantum dalam daftar resmi Pahlawan Nasional Indonesia. Absensi ini menggarisbawahi adanya kontroversi dan ambiguitas yang menyelimuti figur sejarah ini, terutama terkait keputusannya untuk menyerah kepada Belanda. Laporan ini bertujuan untuk menyajikan sebuah analisis komprehensif mengenai kehidupan dan legasi Sentot Prawirodirjo, menelusuri berbagai sumber untuk membentangkan narasi yang seimbang, mengkaji berbagai perspektif yang saling bertentangan, dan memberikan interpretasi mendalam terhadap tindakan serta motivasi kompleks yang mendasari perjalanan hidupnya yang luar biasa.
Terbentuk dalam Bara Pemberontakan – Asal-Usul dan Masa Muda
Untuk memahami kompleksitas Sentot Prawirodirjo, penelusuran harus dimulai dari asal-usul dan tahun-tahun formatifnya, yang ditempa oleh tragedi keluarga, pertalian darah dengan kaum bangsawan pejuang, dan penolakan pribadi terhadap jalur kehidupan yang telah disiapkan untuknya.
Silsilah dan Hubungan dengan Keraton Nama lengkapnya adalah Sentot Ali Basya Abdullah Mustafa Prawirodirjo, sebuah nama yang sarat dengan gelar dan kehormatan. Ia lahir dengan nama Abdul Mustopo Prawirodirjo, atau beberapa catatan menyebutnya Raden Bagus Sentot atau Raden Dullah Prawirodirdjo. Ia adalah putra dari Raden Ronggo Prawirodirjo III, Bupati Wedana Madiun yang dikenal sebagai seorang patriot gigih menentang pemerintah kolonial. Perlawanan ayahnya berakhir tragis pada tahun 1810, ketika ia tewas dalam sebuah pemberontakan melawan pasukan Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels. Ibu Sentot adalah seorang garwa paminggir (selir) ayahnya, dikenal dengan nama Nyi Mas Ajeng Genosari atau Dayawati.
Garis keturunannya terhubung erat dengan lingkaran elite Keraton Yogyakarta. Nenek dari pihak ayahnya adalah seorang putri dari Sultan Hamengkubuwono I, yang menjadikan Sentot sebagai cicit (buyut) dari pendiri Kesultanan Yogyakarta tersebut, sebuah status darah yang setara dengan Pangeran Diponegoro. Hubungan personalnya dengan Diponegoro semakin dipererat melalui ikatan pernikahan. Kakak perempuan Sentot, Raden Ayu Maduretno, merupakan istri sah kedua Pangeran Diponegoro. Setelah pernikahan mereka pada 28 September 1814, Sentot yang kala itu baru berusia sekitar 6 tahun, ikut pindah dan dibesarkan dalam lingkungan keluarga Pangeran Diponegoro di Tegalrejo.
Masa Muda dan Penolakan Pendidikan Formal Lingkungan Tegalrejo, yang menjadi pusat spiritual dan intelektual Pangeran Diponegoro, seharusnya menjadi kawah candradimuka bagi Sentot untuk menjadi seorang alim ulama. Pangeran Diponegoro sendiri berupaya keras untuk mendidiknya sebagai seorang santri di pesantren. Namun, upaya ini ditolak mentah-mentah oleh Sentot muda. Ia menunjukkan "ketidaksukaan yang keras" terhadap pendidikan formal keagamaan.
Alih-alih menekuni kitab, ia lebih memilih menghabiskan waktunya di istal kuda milik Pangeran Diponegoro yang luas. Ia menunjukkan bakat dan gairah yang luar biasa sebagai penunggang kuda dan pembalap, sebuah keahlian yang kelak menjadi aset tak ternilai di medan perang. Penolakannya terhadap pendidikan formal membuatnya dilaporkan buta huruf, sebuah kekurangan yang di kemudian hari memberinya kesulitan saat ia dibebani tanggung jawab administrasi dan keuangan.
Kematian ayahnya di tangan Belanda menanamkan benih dendam yang mendalam, sementara kedekatannya dengan Pangeran Diponegoro menumbuhkan semangat perlawanan anti-kolonial dalam dirinya. Meskipun ia menolak jalan hidup sebagai santri, ia tak pelak menyerap ideologi perjuangan (jihad) yang diusung oleh Diponegoro. Kecenderungan alaminya pada aktivitas fisik dan strategi militer, yang terasah melalui kegemarannya berkuda, menemukan wadah yang sempurna ketika Perang Jawa meletus. Ini bukanlah sebuah kebetulan, melainkan konvergensi antara trauma pribadi, lingkungan ideologis, dan bakat alami yang membentuk takdirnya sebagai seorang komandan perang.
Panglima Muda dalam Perang Jawa (1825-1830)
Pecahnya Perang Jawa pada tahun 1825 menjadi panggung bagi Sentot Prawirodirjo untuk membuktikan takdirnya. Dalam waktu singkat, ia bertransformasi dari seorang pemuda bangsawan yang berapi-api menjadi salah satu komandan militer paling disegani dalam sejarah peperangan di Nusantara.
Kebangkitan 'Ali Basya' Ketika Pangeran Diponegoro mengobarkan perlawanan, Sentot yang kala itu baru berusia 17 tahun tanpa ragu bergabung dengan barisan pejuang di Gua Selarong pada Agustus 1825. Bakat militernya yang luar biasa segera terlihat. Setelah tiga tahun bertempur dengan gagah berani, pada tahun 1828, ia diangkat menjadi Senopati atau Panglima Perang Tertinggi pasukan Diponegoro. Pengangkatan ini terjadi setelah panglima sebelumnya, Gusti Basyah, gugur di medan perang. Sebelum wafat, Gusti Basyah berwasiat dan merekomendasikan agar Sentot yang menggantikannya, sebuah usulan yang disetujui oleh Pangeran Diponegoro.
Bersamaan dengan jabatan tersebut, Pangeran Diponegoro menganugerahinya gelar kehormatan "Ali Basya". Gelar ini, yang kemungkinan besar terinspirasi dari pangkat komandan militer "Ali Pasha" di Kesultanan Utsmaniyah Turki, merupakan simbol pengakuan atas keberaniannya dan melambangkan kebanggaan umat Islam pada masa itu. Nama panggilannya yang paling terkenal, "Sentot," adalah sebuah nom de guerre (nama perang) yang dalam bahasa Jawa berarti "melesat" atau "meloloskan diri," sebuah julukan yang mencerminkan karakternya yang kompleks, sulit ditebak, dan gerakannya yang lincah di medan perang.
Ahli Taktik Gerilya Sebagai panglima, Sentot membentuk dan memimpin sebuah pasukan kavaleri khusus yang menjadi ujung tombak kekuatan Diponegoro. Pasukan ini terdiri dari sekitar 1.000 prajurit berkuda, semuanya mengenakan sorban sebagai identitasnya, dan berspesialisasi dalam taktik serangan kilat (blitzkrieg), cepat, dan mematikan. Pasukannya murni kavaleri, tanpa unit infanteri, yang memungkinkan mobilitas superior dalam perang gerilya.
Di bawah komandonya, pasukan ini meraih serangkaian kemenangan gemilang yang membuat Belanda kewalahan. Beberapa pertempuran heroik yang tercatat antara lain keberhasilannya memukul mundur pasukan Belanda di Nanggulan, Kulon Progo, yang menewaskan komandan Belanda, Kapten Ingen. Ia juga berhasil memukul mundur pasukan yang dipimpin oleh Sollewijn di Progo Timur pada September 1828 dan secara telak menghancurkan satu kolom penuh pasukan Belanda dalam sebuah penyergapan di Kroya pada tahun yang sama. Keberanian dan kecerdasan taktisnya diakui secara luas, bahkan oleh pihak Belanda sendiri. Seorang perwira Belanda menggambarkannya sebagai "pemimpin pemberontak yang memiliki keberanian dan gaya bertarung terbaik", sementara sejarawan kolonial mencatat bahwa manuver-maneuvernya di lapangan mampu "mencengangkan para lawannya dengan kemahiran dan keberanian yang luar biasa".
Beban Komando dan Isu Finansial Di puncak kejayaannya, pada Desember 1828, Sentot menghadap Pangeran Diponegoro dengan sebuah permintaan yang kontroversial. Ia meminta wewenang penuh untuk memimpin seluruh kekuatan militer dan, yang lebih penting, untuk mengelola penarikan pajak secara langsung dari rakyat di wilayah yang dikuasai pejuang, dengan dalih untuk membiayai kebutuhan logistik pasukannya.
Permintaan ini menimbulkan kegelisahan mendalam pada Pangeran Diponegoro. Sebagai pemimpin yang mengusung citra Ratu Adil (Raja yang Adil) dengan janji kebijakan pajak yang ringan, Diponegoro khawatir wewenang tersebut akan disalahgunakan. Kekhawatiran ini beralasan, mengingat Sentot dikenal memiliki gaya hidup boros. Dalam otobiografinya, Babad Diponegoro, Pangeran Diponegoro menuliskan kegundahannya: "Jika ia yang memegang pedang, juga diperbolehkan menggenggam uang, lantas bagaimana? Tidakkah itu membuat terbengkalai?".
Meskipun dengan berat hati Diponegoro akhirnya menyetujui, memberikan Sentot hak atas dua pertiga pajak cukai pasar di beberapa wilayah, kekhawatiran itu terbukti menjadi kenyataan. Beban administrasi keuangan, sebuah bidang yang tidak ia kuasai mengingat ia buta huruf, membuat fokus militernya terpecah. Akibatnya, ia menjadi lamban dalam bereaksi terhadap gerakan pasukan Belanda. Kelalaian fatal ini terjadi pada Januari 1829. Ketika Belanda membangun sebuah benteng baru yang besar di Nanggulan, Sentot tidak segera memerintahkan penyerangan karena terlalu sibuk dengan urusan keuangan. Saat serangan akhirnya dilancarkan, benteng tersebut sudah terlanjur kokoh, dan pasukan Sentot harus menelan kekalahan besar.
Kekalahan ini bukan hanya kerugian militer, tetapi juga menjadi titik awal dari keretakan hubungan antara Diponegoro, Sentot, dan rakyat. Persoalan pajak mulai merusak kepercayaan rakyat, padahal dukungan mereka adalah napas dari perang gerilya. Rangkaian peristiwa ini menunjukkan bahwa kejatuhan militer Sentot tidak hanya disebabkan oleh kekuatan musuh, tetapi juga dipicu oleh faktor internal yang berakar pada ambisinya sendiri. Permintaannya untuk mengontrol keuangan, meskipun mungkin didasari oleh kebutuhan logistik yang nyata, secara langsung menyebabkan kelalaian strategis yang fatal dan menjadi awal dari akhir perjuangannya di tanah Jawa.
Persimpangan Jalan: Analisis Penyerahan Diri Tahun 1829
Keputusan Sentot Prawirodirjo untuk menyerah kepada Belanda pada 16 Oktober 1829 merupakan momen paling kontroversial dalam hidupnya dan menjadi titik perdebatan utama di kalangan sejarawan. Peristiwa ini tidak dapat dilihat secara hitam-putih sebagai sebuah pengkhianatan atau kapitulasi sederhana. Sebaliknya, ia merupakan sebuah keputusan kompleks yang lahir dari persimpangan antara tekanan militer, manuver politik, dan pertimbangan personal. Untuk memahaminya, perlu dianalisis berbagai narasi yang ada.
Narasi Negosiasi Strategis Berbeda dengan gambaran penyerahan tanpa syarat, proses yang dijalani Sentot lebih menyerupai sebuah negosiasi politik. Jenderal De Kock, panglima tertinggi Belanda, tidak semata-mata mengandalkan kekuatan militer, melainkan menerapkan "pendekatan keluarga" yang cerdik. Ia memanfaatkan Pangeran Raden Ronggo Prawirodiningrat, Bupati Madiun yang merupakan kakak tiri Sentot, untuk membujuknya agar mau berunding.
Sentot tidak menyerah begitu saja. Ia mengajukan serangkaian syarat yang tegas sebagai prasyarat penghentian perlawanannya. Syarat-syarat tersebut antara lain:
Ia dan pasukannya diizinkan untuk tetap memeluk agama Islam dan mengenakan identitas mereka (sorban dan jubah).
Pasukannya yang berjumlah sekitar 1.000 orang tidak dibubarkan dan tetap berada di bawah komandonya.
Pemberian jaminan finansial sebesar 10.000 dolar/ringgit dan pasokan persenjataan.
Statusnya sebagai komandan pasukan akan berada langsung di bawah pemerintah kolonial, bukan di bawah Sultan atau penguasa lokal lainnya.
Pihak Belanda, yang sangat ingin mengakhiri perang yang menguras sumber daya, menyetujui sebagian besar syarat tersebut. Mereka mengangkat Sentot menjadi perwira di dinas militer Belanda dengan pangkat Letnan Kolonel, lengkap dengan gaji dan fasilitas. Proses negosiasi yang alot ini menunjukkan bahwa penyerahan diri Sentot adalah sebuah kompromi strategis, di mana ia berhasil mengamankan posisi, pasukan, dan kebebasan beragama bagi dirinya dan para pengikutnya.
Narasi Pengkhianatan dan Kepentingan Pribadi Narasi yang lebih populer, terutama yang disebarkan melalui artikel-artikel berita, cenderung melabeli tindakan Sentot sebagai pengkhianatan yang didorong oleh motif pribadi. Ia dituduh "tergoda uang" dan lebih mementingkan keuntungan pribadi daripada perjuangan. Tuduhan ini diperkuat oleh fakta bahwa sebelum kekalahan fatal di Nanggulan, ia memang sedang sibuk mengurusi masalah keuangan pasukan. Perilaku ini menciptakan citra bahwa ia telah kehilangan fokus pada tujuan perang dan lebih memprioritaskan materi, sehingga penyerahannya dilihat sebagai puncak dari keserakahannya.
Narasi Pragmatisme dan Kemanusiaan Perspektif ketiga menawarkan pandangan yang lebih simpatik. Menurut narasi ini, keputusan Sentot dimotivasi oleh alasan kemanusiaan. Setelah bertahun-tahun berperang, ia tidak sanggup lagi menyaksikan penderitaan rakyat Jawa yang semakin parah. Kondisi perekonomian hancur, dan warga sipil, yang menjadi penyuplai utama logistik bagi para pejuang, menanggung beban terberat. Dalam konteks ini, setelah pasukannya mengalami kekalahan besar dan dukungan rakyat mulai memudar, penyerahan diri dapat diinterpretasikan sebagai pilihan pragmatis untuk mengakhiri pertumpahan darah dan penderitaan yang lebih luas.
Ketiga narasi ini kemungkinan besar tidak saling meniadakan, melainkan saling melengkapi untuk membentuk gambaran yang lebih utuh. Penyerahan diri Sentot adalah sebuah manuver politik yang lahir dari kalkulasi rasional di tengah situasi yang sulit. Tekanan militer yang berat setelah kekalahan di Nanggulan dan pertempuran Siluk membuatnya sadar bahwa opsi kemenangan semakin menipis. Di saat yang sama, penderitaan rakyat memberinya justifikasi kemanusiaan yang kuat. Ketika Belanda datang dengan tawaran negosiasi yang menguntungkan—bukan penaklukan total—Sentot, yang telah menunjukkan ambisi untuk berkuasa, melihat sebuah peluang. Ia dapat menyelamatkan dirinya, pasukannya, dan mengamankan masa depan melalui sebuah kompromi yang dibungkus dengan alasan mulia. Ini bukanlah pengkhianatan sederhana, melainkan sebuah aksi politik multimotivasi dari seorang komandan yang cerdik namun terjepit.
Seragam Baru, Loyalitas Lama? – Pengabdian di Tentara Kolonial
Babak kehidupan Sentot setelah menyerah kepada Belanda adalah salah satu yang paling menarik dan paling jelas menunjukkan kelihaian strateginya. Dengan mengenakan seragam Letnan Kolonel Belanda, ia tidak mengakhiri perjuangannya, melainkan mengubah metodenya secara radikal.
Muslihat dalam Perang Padri Setelah resmi bergabung dengan militer kolonial, Sentot dan unitnya yang terdiri dari 450 prajurit Jawa pertama kali ditugaskan untuk menumpas kerusuhan para migran Tionghoa di Purwakarta pada tahun 1832. Ia menjalankan tugas ini dengan efektif dan bahkan mendapat pujian dari komandan Belanda. Keberhasilan ini membuat Belanda semakin percaya padanya.
Kepercayaan inilah yang kemudian menjadi bumerang bagi Belanda. Pada tahun 1833, Sentot dan pasukannya dikirim ke front yang jauh lebih besar: Sumatera Barat, untuk membantu Belanda menumpas perlawanan sengit dari Kaum Padri yang dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol. Namun, setibanya di sana, niat Sentot berubah. Ia menyadari bahwa semangat perjuangan Kaum Padri—sebuah perang jihad melawan penjajah kafir untuk menegakkan keadilan—sama persis dengan semangat yang pernah ia kobarkan bersama Pangeran Diponegoro.
Alih-alih memerangi Kaum Padri, Sentot justru secara diam-diam menjalin persekutuan dengan mereka. Ia mengadakan pertemuan rahasia dengan Tuanku Imam Bonjol dan tokoh adat Minangkabau, Sultan Alam Bagagarsyah, untuk merancang strategi bersama mengusir Belanda dari Minangkabau. Ia memainkan peran ganda yang sangat berbahaya: di satu sisi ia adalah perwira Belanda, di sisi lain ia adalah pemasok informasi dan persenjataan bagi musuh Belanda. Dengan memanfaatkan sumber daya, logistik, dan senjata yang diberikan oleh pemerintah kolonial, ia secara efektif membantu perjuangan Kaum Padri dari dalam. Tindakannya ini mengubah statusnya dari yang semula dikirim sebagai "penghancur Padri" menjadi "pahlawan bagi Padri".
Terbongkarnya Permainan Ganda Muslihat cerdik Sentot tidak bertahan selamanya. Pemerintah kolonial Belanda, yang mulai curiga dengan kegagalan beruntun di front Padri dan laporan intelijen, akhirnya mencium permainan gandanya. Ketika pertempuran kembali pecah di wilayah Bonjol, Sentot dijadikan kambing hitam dan ditangkap oleh Belanda.
Akibat dari pengkhianatannya terhadap Belanda, ia segera dicopot dari jabatannya sebagai komandan. Pasukan setianya yang berasal dari Jawa dibubarkan dan kemudian dilebur ke dalam tentara reguler kolonial, Koninklijk Nederlandsch-Indische Leger (KNIL). Sentot sendiri dibawa kembali ke Batavia untuk diadili atas tuduhan insubordinasi dan kolusi dengan musuh. Episode ini menandai akhir dari karier militernya dan menjadi gerbang menuju babak terakhir dalam hidupnya: pengasingan.
Peristiwa di Sumatera Barat ini memberikan bobot yang sangat kuat pada argumen bahwa penyerahan diri Sentot pada tahun 1829 bukanlah akhir dari perjuangannya, melainkan sebuah taktik jangka panjang yang brilian. Syarat yang ia ajukan saat menyerah—terutama agar pasukannya tetap utuh dan bersenjata—kini terlihat sebagai bagian dari sebuah rencana besar. Ia seolah-olah menipu Belanda untuk membiayai dan mempersenjatai kelanjutan perjuangan anti-kolonialnya di front yang berbeda. Ini menunjukkan tingkat kecerdasan strategis dan komitmen ideologis yang jauh melampaui sekadar kepentingan pribadi, membingkai ulang citranya dari seorang yang menyerah menjadi seorang ahli strategi yang mampu berperang dengan cara lain.
Babak Terakhir – Pengasingan dan Warisan di Bengkulu
Setelah pengadilan di Batavia, nasib Sentot Prawirodirjo telah ditentukan. Ia tidak dieksekusi, tetapi dijauhkan secara permanen dari panggung politik dan militer Jawa dan Sumatera. Ia dijatuhi hukuman pengasingan seumur hidup di Bengkulu, sebuah wilayah terpencil di pesisir barat Sumatera. Namun, di tanah pembuangan inilah ia justru menemukan peran baru dan meninggalkan warisan yang tak terduga dan bertahan lama.
Sang Guru di Pengasingan Sentot memulai masa pengasingannya di Bengkulu pada tahun 1833. Sebuah catatan menarik menyebutkan bahwa sebelum diberangkatkan ke Bengkulu, pemerintah kolonial mengizinkannya untuk menunaikan ibadah haji ke Mekkah, sebuah gestur yang mungkin bertujuan untuk meredam potensi kemarahan dari pengikutnya. Selama kurang lebih 22 tahun hidup sebagai orang buangan, ia bertransformasi dari seorang panglima perang menjadi seorang guru dan tokoh spiritual.
Jauh dari hiruk pikuk pertempuran, ia mendedikasikan sisa hidupnya untuk menyebarkan ajaran Islam. Ia menjadi sosok yang sangat dihormati oleh masyarakat setempat, mengajarkan berbagai ilmu dan kaidah agama kepada penduduk Bengkulu. Peran barunya ini menunjukkan sisi lain dari karakternya, di mana setelah gagal dalam perjuangan bersenjata, ia kembali ke akar ideologis perjuangannya melalui jalan dakwah dan pendidikan.
Sentot Ali Basya Prawirodirjo wafat pada tanggal 17 April 1855, menurut mayoritas catatan sejarah. Ia dimakamkan di sebuah pemakaman umum di Kelurahan Bajak, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu. Namun, sebuah misteri sejarah menyelimuti tanggal wafatnya, karena pada batu nisannya tertera tahun 1885, berbeda 30 tahun dari catatan yang ada. Inkonsistensi ini hingga kini belum terpecahkan dan menambah lapisan misteri pada sosoknya.
Jejak Budaya yang Abadi Pengaruh Sentot di Bengkulu tidak hanya terbatas pada bidang spiritual. Kehadirannya bersama para pengikutnya dari Jawa meninggalkan jejak budaya yang konkret dan menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas Bengkulu.
Salah satu warisan terpentingnya adalah keterkaitannya dengan perkembangan Batik Besurek. Banyak sumber sejarah dan tradisi lisan menyebutkan bahwa para perajin dan pemakai awal batik khas Bengkulu ini adalah para pengikut dan keturunan Sentot yang ikut diasingkan. Nama "Besurek" sendiri berarti "bersurat" atau "bertulis," merujuk pada motif utamanya yang berupa kaligrafi Arab. Motif yang kental dengan nuansa Islam ini sangat selaras dengan citra Sentot sebagai seorang pemimpin Muslim dan perannya sebagai penyebar agama di Bengkulu.
Selain itu, makamnya telah menjadi sebuah situs penting. Jauh dari kesan terabaikan, makam Sentot telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota melalui Surat Keputusan pada tahun 2009. Kini, makam tersebut menjadi salah satu destinasi wisata sejarah dan religi utama di Kota Bengkulu, yang sering dikunjungi peziarah dan wisatawan. Kompleks makam ini bahkan sering menjadi pusat kegiatan budaya lokal, seperti tradisi Sarafal Anam (seni lantunan syair berzanji). Arsitektur cungkup makamnya yang unik, yang disebut bergaya "Tabot," juga merupakan cerminan dari akulturasi budaya di Bengkulu.
Di pengasingan, identitas Sentot Prawirodirjo mengalami sebuah transformasi fundamental. Setelah karier militer dan politiknya dipaksa berakhir, ia menemukan sebuah peran baru yang tak kalah penting sebagai seorang guru spiritual dan ikon budaya. Jika di Jawa legasinya adalah legasi militer yang kompleks dan ambigu, maka di Bengkulu legasinya adalah warisan spiritual dan budaya yang positif, dihormati, dan terus hidup hingga hari ini. Ini dapat dilihat sebagai sebuah babak penebusan dalam narasi hidupnya yang penuh gejolak.
Kesimpulan: Mengevaluasi Kembali Sentot Prawirodirjo – Pahlawan, Pengkhianat, atau Pragmatis?
Perjalanan hidup Sentot Ali Basya Abdullah Mustafa Prawirodirjo, dari seorang panglima muda yang jenius di medan Perang Jawa, menjadi seorang negosiator yang terjepit, lalu agen ganda yang cerdik dalam Perang Padri, hingga akhirnya menjadi seorang guru yang dihormati di pengasingan, menunjukkan bahwa ia adalah sosok yang tidak dapat dikategorikan secara sederhana. Melabelinya sebagai "pahlawan" murni atau "pengkhianat" mutlak adalah sebuah penyederhanaan yang mengabaikan kompleksitas situasi dan kecerdasan strateginya. Ia lebih tepat digambarkan sebagai seorang pragmatis revolusioner: seorang pejuang yang berkomitmen pada agenda anti-kolonial, namun bersedia menggunakan berbagai cara—termasuk kompromi dan muslihat yang kontroversial—untuk bertahan dan melanjutkan perjuangannya.
Analisis ini membawa pada jawaban atas pertanyaan krusial mengenai status kepahlawanannya. Secara faktual, Sentot Prawirodirjo tidak terdaftar sebagai Pahlawan Nasional Indonesia. Alasan utama di balik ini terletak pada ambiguitas tindakannya. Keputusannya untuk menyerah dan menerima pangkat Letnan Kolonel dari Belanda, meskipun dapat diinterpretasikan sebagai taktik jangka panjang, telah menciptakan sebuah "aib" atau catatan cacat dalam narasi kepahlawanannya. Sejarah kepahlawanan nasional seringkali menuntut sebuah narasi yang konsisten, tanpa kompromi, dan heroik secara linear. Tindakan Sentot yang kompleks dan multi-interpretasi menyulitkan pembentukan narasi semacam itu. Usulan untuk mengangkatnya sebagai pahlawan nasional pun diakui menghadapi kendala karena "simpang siurnya sejarah" yang menyelimuti dirinya.
Meskipun demikian, ketiadaan gelar resmi tidak mengurangi signifikansi historis Sentot Prawirodirjo. Ia adalah representasi hidup dari dilema dan kompleksitas perjuangan melawan kolonialisme, di mana garis antara perlawanan, kompromi, strategi, dan kelangsungan hidup seringkali kabur. Warisannya tidak hanya terukir dalam catatan-catatan militer Perang Jawa yang mengisahkan kehebatannya, tetapi juga hidup dalam denyut nadi budaya masyarakat Bengkulu melalui ajaran Islam yang ia sebarkan dan keindahan motif kaligrafi pada Batik Besurek. Sentot Prawirodirjo mungkin bukan pahlawan dalam bingkai formal negara, tetapi ia tetaplah seorang tokoh besar yang perannya dalam membentuk sejarah perlawanan dan budaya di Nusantara tidak terbantahkan.





















 Politik
Politik Konser
Konser Makanan
Makanan Olahraga
Olahraga Pariwisata
Pariwisata Pemerintahan
Pemerintahan Anak Muda
Anak Muda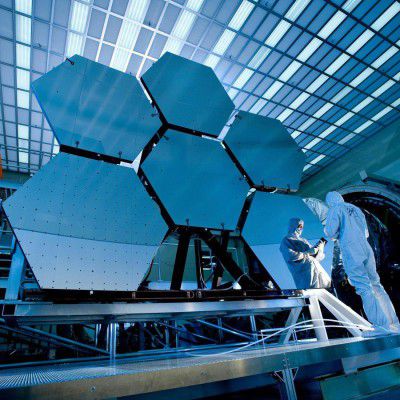 Teknologi
Teknologi Transportasi
Transportasi
0 Comments